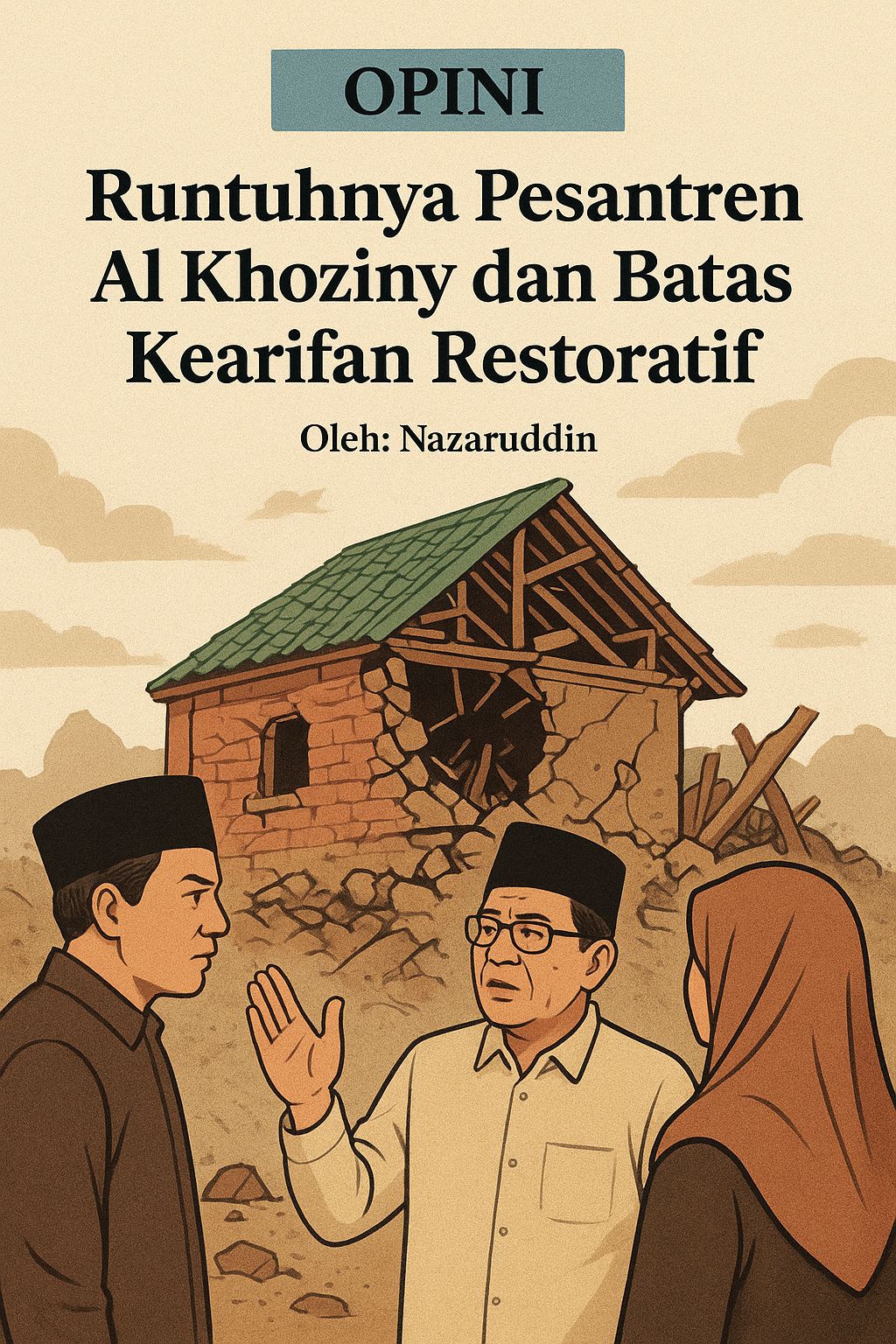Opini – Redaksi86.COM – Prof. Mahfud MD menyatakan bahwa kasus runtuhnya bangunan Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo harus diselesaikan melalui pendekatan hukum dan kearifan. Penegakan hukum, katanya, tidak boleh dihalangi, tetapi harus dilakukan dengan memahami tradisi pesantren sebagai kearifan. Solusinya: restorative justice — keadilan yang berorientasi pada pemulihan, bukan pembalasan.
Gagasan ini terdengar bijak. Namun dalam praktik, ia menyisakan pertanyaan serius: Apakah kasus kelalaian yang menimbulkan korban jiwa layak diselesaikan dengan pendekatan restoratif?
Antara Pemulihan dan Akuntabilitas
Restorative justice bukan sekadar mediasi damai. Ia merupakan pendekatan hukum yang berfokus pada pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, dan rekonsiliasi sosial. Dalam kerangka hukum positif Indonesia, mekanisme ini diatur dalam Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2024.
Namun, keadilan restoratif hanya dapat diterapkan bila memenuhi syarat tertentu: ancaman pidana tidak lebih dari lima tahun, pelaku menunjukkan penyesalan dan itikad baik, korban atau keluarganya bersedia berdamai, dan peristiwa tersebut tidak menimbulkan keresahan publik.
Kasus kelalaian yang menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP) — apalagi dengan jumlah korban puluhan logikanya melampaui batas hukuman lima tahun dan sulit untuk dihentikan penuntutannya hanya dengan mediasi. Secara moral dan sosial, perkara ini juga tidak sederhana.
Kearifan yang Menjadi Tameng
Kita harus hati-hati agar “kearifan lokal pesantren” tidak berubah menjadi tameng bagi impunitas. Mengedepankan dialog dan kekeluargaan memang mulia, tetapi tidak boleh menghapus prinsip akuntabilitas. Ketika nyawa santri melayang akibat kelalaian teknis — entah karena bangunan tak memenuhi standar, pengawasan yang lalai, atau prosedur izin yang diabaikan — maka keadilan tidak cukup dipulihkan dengan maaf dan kompensasi.
Kearifan, dalam makna sejatinya, adalah kebijaksanaan yang menguatkan keadilan, bukan menggantikannya. Jika “kearifan” dijadikan alasan untuk menghindari tanggung jawab hukum, maka kita sedang melahirkan feodalisme baru dalam ruang keagamaan — di mana kesalahan dimaafkan bukan karena iktikad baik, tetapi karena status sosial pelakunya
Bahaya Menormalisasi Kelalaian
Jika keadilan restoratif diterapkan tanpa transparansi dan evaluasi yang jujur, maka ia justru bisa menjadi jalan sunyi bagi ketidakadilan. Masyarakat akan menafsirkan bahwa ketika pelanggaran terjadi di institusi keagamaan, hukum menjadi lunak. Ini sangat berbahaya bagi prinsip kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law).
Tragedi di Al Khoziny bukan sekadar “musibah” yang harus diterima dengan ikhlas. Ia adalah peringatan atas kelalaian sistemik — bagaimana pembangunan bisa dilakukan tanpa standar, tanpa akuntabilitas, dan kemudian dibungkus dengan narasi takdir. Dalam situasi seperti ini, restorative justice hanya bermakna jika dijalankan dengan pengakuan kesalahan, pemulihan korban, dan perubahan struktural agar tidak terulang kembali.
Restoratif yang Berkeadilan
Keadilan restoratif bisa menjadi jalan mulia bila diterapkan dengan transparan, jujur, dan berorientasi pada tanggung jawab moral serta hukum. Tapi ia kehilangan maknanya bila dijadikan alat untuk menutupi kesalahan.
Prof. Mahfud benar: hukum harus berjalan, dan kearifan harus dihargai. Namun, kearifan tanpa akuntabilitas adalah pembenaran atas kelalaian.
Kasus Al Khoziny adalah ujian apakah bangsa ini masih sanggup menegakkan keadilan tanpa kehilangan empati — dan mempraktikkan empati tanpa menafikan keadilan.
Penulis : Nazaruddin